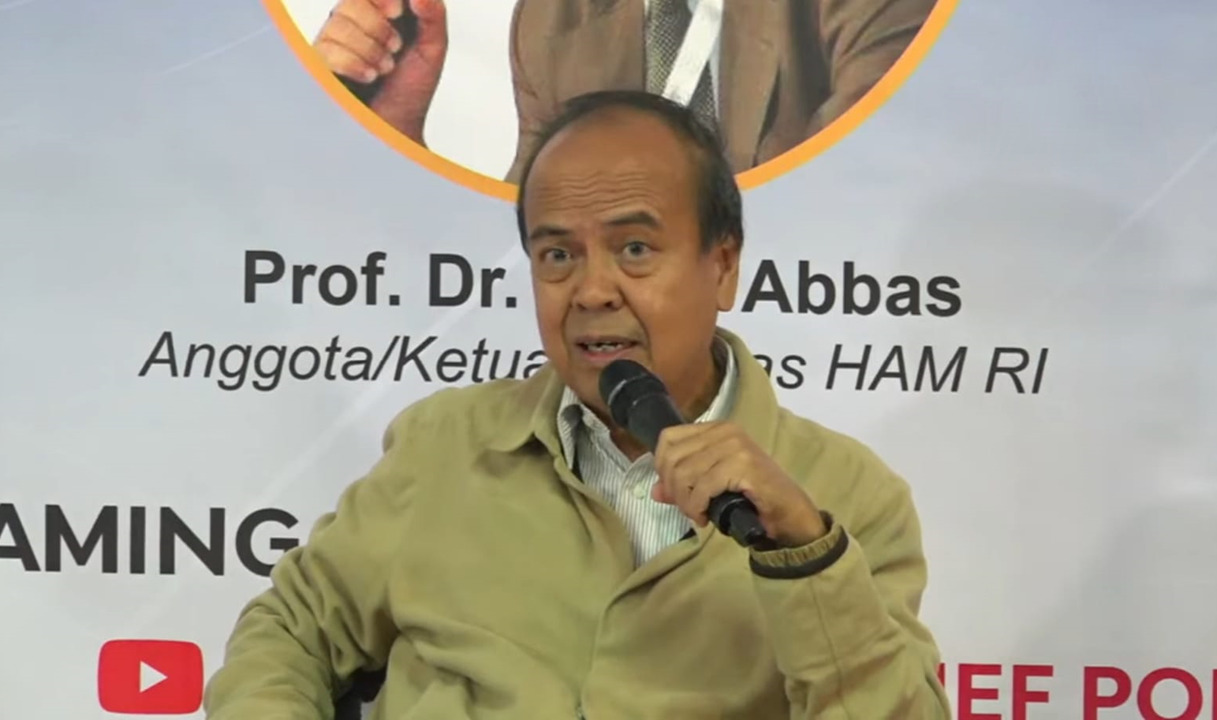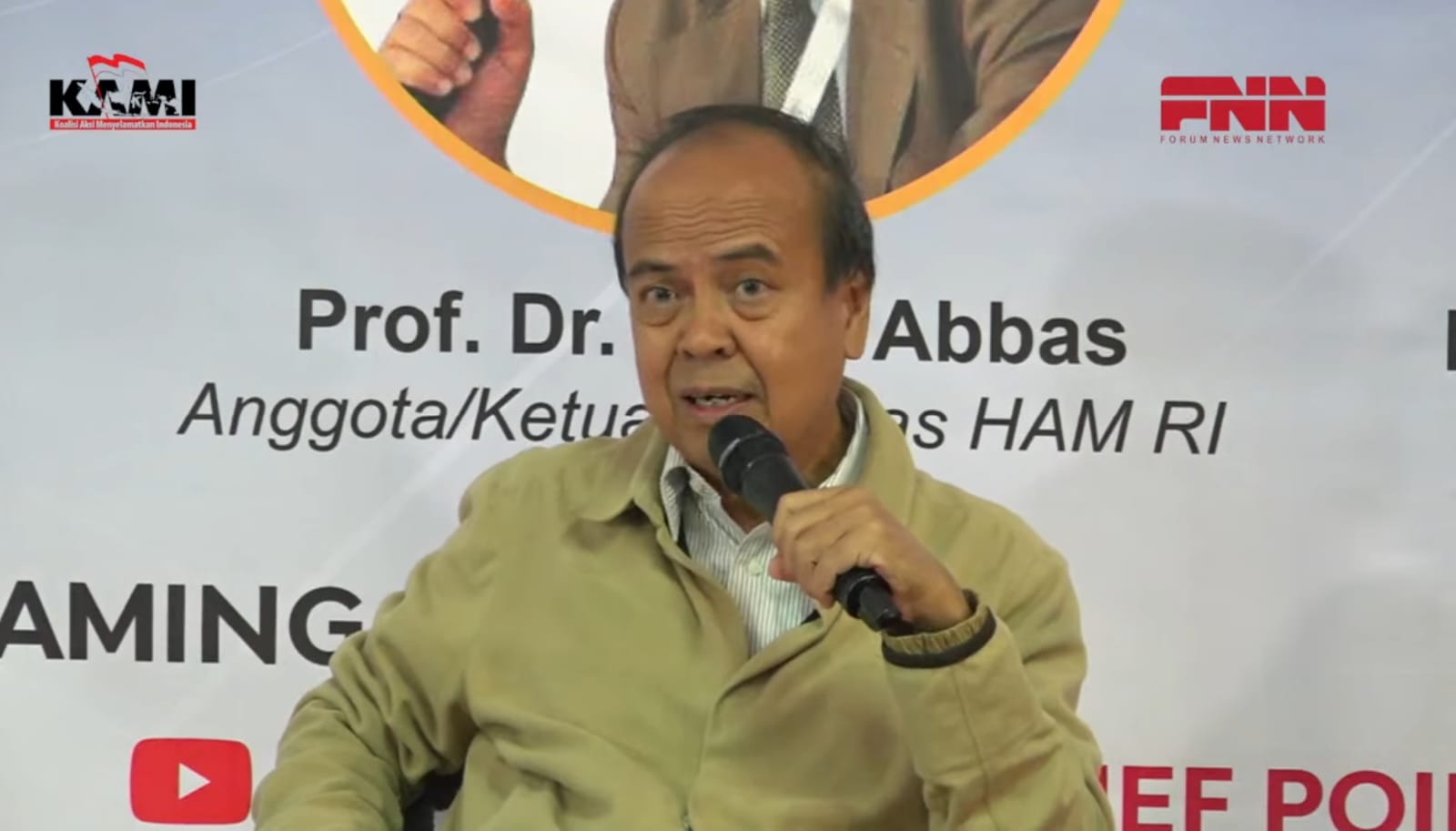Oleh : Prof. Dr. Hafid Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM RI)
Kelihatannya dalam satu dekade terakhir ini, kasus mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo adalah kasus yang paling banyak disoroti publik. Media telah amat berjasa memviralkan kasus Sambo ke seluruh pelosok negeri tanpa henti dalam beberapa minggu terakhir. Ini bermula dari pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yoshua pada 8 Juli 2022, di rumah dinas Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren Tiga Jakarta Selatan.
Penyebab tewasnya Yoshua pada awalnya disebut karena ia saling tembak menembak dengan Bharada Elizer. Kasus ini kemudian bergulir, mulanya motifnya diduga dipicu oleh adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yoshua terhadap isteri Sambo. Namun belakangan motif pelecehan itu dikesampingkan setelah ditetapkannya Sambo sebagai tersangka oleh Kapolri Jenderal Listryo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yoshua.
Kasus ini kini semakin meluas dan membesar, dan belum jelas kapan akan berakhir. Kini sudah 83 orang anggota Polri yang telah diperiksa, ada perwira tinggi (Pati), perwira menengah (Pamen), dan perwira pertama. Dari jumlah itu, 18 di antaranya sudah ditahan, 35 lainnya direkomendasikan juga ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua (wartaekonimi, 20/8/2022).
Realitas rekayasa kasus ini seakan menyentakkan kesadaran publik ke trauma masa lalu atas sejumlah kasus lain yang dinilai juga sarat dengan rekayasa, seperti: kematian Suyono, terduga teroris, dan kasus-kasus teroris lainnya; kematian 894 petugas KPPS dan 5175 petugas lainnya yang jatuh sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019; kasus KM50 yang telah menewaskan enam orang laskar FPI; dst.
Dari kasus Sambo ini terlihat urgensi untuk menata kembali kelembagaan Polri yang saat ini terlihat berada di zona segitiga kekuasaan.
Kepolisian di zona segitiga kepentingan
Sejak Indonesia memilih jalan demokrasi dan desentralisasi di penghujung abad ke-20, kelihatannya corak kepemimpinan di pusat dan daerah diatur oleh Hukum Darwin, “survival of the fittest,” yang kuatlah yang pasti menang dan yang lemah akan punah.
Sebagai ilustrasi, KPK telah mengungkapkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan seseorang agar terpilih menjadi Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) bervariasi antara Rp 20-100 miliar atau rata-rata Rp 60 miliar (Kompas, 23/7/2020).
Di sisi lain gaji pejabat Indonesia 2019-2024, mulai dari Bupati dan Walikota hingga Presiden, terlihat amat rendah. Jika seorang Bupati berpendapatan hanya dari gaji pokok dan tunjangan resminya yang hanya Rp 5,88 juta sebulan (gajimu.com), maka untuk mengembalikan modalnya, ia harus bekerja sebagai Bupati untuk masa kerja 170-171 tahun.
Satu-satunya cara untuk mengembalikan biaya politiknya yang amat mahal itu, adalah dengan merangkul korporasi dengan memberinya hak penguasaan lahan, tambang, dan sumber-sumber daya alam (SDA) setempat, dsb.
Karenanya, jika dihitung jumlah pemberian izin konsesi lahan untuk penguasaan SDA oleh pemerintah pusat dan daerah kepada korporasi, misalnya di Sulawesi Tenggara ternyata luasnya sudah melebihi seluruh luas daratan provinsi itu sendiri. Ini juga terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan provinsi-provinsi lainnya di tanah air (Kompas,21/05/2018).
Bahkan, terdapat 35 juta hektar tanah yang dikuasai oleh beberapa korporasi besar, dan dan terdapat juga 14,6 juta hektar lahan sawit sehingga tanah seluas hampir 50 juta hektar atau 758 kali luas Jakarta, hanya dikuasai oleh beberapa kelompok pengusaha dan manfaatnya pada negara teramat kecil, hanya sekitar Rp 3 triliun setahun; (Kompas,15/03/2018). Ini tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan oleh negara kepada pengusaha sawit yang jauh lebih besar, yakni Rp7,5 triliun dari Januari-September 2017 (CNNIndonesia, 18/01/2018).
Jika masyarakat memprotes setelah digusur karena lahannya harus diberikan ke korporasi atau pemilik modal, maka di sinilah peran kunci polisi untuk menangani gejolak ini. Dampaknya, antara lain:
Pertama, kekerasan yang dialami masyarakat meningkat. KontraS mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat 677 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kekerasan itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus yang telah menyebabkan 59 orang meninggal dunia, 928 luka-luka, dan 1.240 ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus terjadi di tingkat Polsek sebanyak 121, dan di Polda sebanyak 77 kasus (Kompas.com, 30/06/2022).
Kedua, masyarakat mencari tempat mengadu. Sepanjang 2014, Komnas HAM RI menerima 6967 pengaduan masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah tanah air. Mereka mengadukan: polisi 35,6% (2483 kasus), korporasi 1590 kasus (22,8%), Pemda 1270 kasus (18,3%), peradilan dan kejaksaan 836 (12%), dan selebihnya lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa 88,7% kasus pelanggaran HAM di tanah air, aktor utamanya adalah polisi, korporasi dan Pemda.
Hingga saat ini, fotret pelaku pelanggaran HAM ini belum berubah. Institusi kepolisian tetap berada pada pososi tertinggi yang diadukan oleh masyarakat.
Komnas HAM lebih jauh menelaah substansi setiap pengaduan masyarakat, dan ditemukan 43,2% (3011 kasus) terkait dengan hilangnya hak masyarakat memperoleh keadilan; 42,5% (2959 kasus) menyatakan hilangnya hak mereka atas kesejahteraan karena tanah mereka sebagai sumber kehidupannya telah dirampas; dan hilangnya rasa aman warga sebesar 12,5% (871 kasus).
Data ini menunjukkan bahwa 98,2% keresahan masyarakat terkait dengan hilangnya ketiga hak dasar itu, dan kepolisian berkontribusi 35,6% atas hilangnya hak-hak itu.
Indonesia Terancam Bubar
Salah satu dampak dari hilangnya keadilan, sumber nafkah dan rasa aman bagi masyarakat kecil, jurang kaya-miskin di negeri ini terlihat semakin hari semakin membesar. Oxfam menyebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin (2017). Bahkan kekayaan 50 WNI kelas atas menguasai lebih 48% total GDP atau 72% dari total APBN 2021 yang mencapai 2750 triliun rupiah (Jakarta Post, 18/12/2020).
Bertolak dari gambaran ini, Bank Dunia memperkirakan Indonesia pada akhirnya akan bubar. Dalam publikasinya, Indonesia Rising Divide (2016, hal.28), terdapat empat sumber penyebab pecahnya NKRI.
Pertama, adanya ketidaksamaam pemberian kesempatan kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kemapuannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, ada pihak diberi kesempatan menguasai jutaan hektar lahan, sementara pada 2016 orang miskin di DKI Jakarta, misalnya, digusur sebanyak 193 kali setahun (Tempo, 13/04/2017).
Kedua, kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing dengan kelas masyarakat atas di sektor ekonomi modern. Mereka hanya dapat diserap di sektor informal yang berupah amat rendah.
Ketiga, kosentrasi peredaran uang dan modal di negeri ini hanya berputar di beberapa orang atau beberapa perusahaan. Misalnya, terdapat 56.534.592 UMKM (99,99%) yang tidak tersentuh dengan bantuan perbankkan (Data BUMN, 2019).
Keempat, orang miskin ini tidak memiliki tabungan untuk membiayai pendidikan anak dan keturunannya, dan juga tidak memiliki tabungan untuk biaya kesehatannya di hari tuanya.
Dengan gambaran itu, pandangan Prabowo Subianto kelihatannya cukup beralasan jika dikatakan Indonesia sudah tidak ada lagi pada 2030 (BBC, 24/03/2018).
Mencari Solusi
Beragam upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kemuliaan institusi kepolisian pasca kasus Sambo, antara lain.
Pertama, apa yang telah dilakukan oleh Jend. M Jusuf ketika memimpin TNI-Polri di era Odre Baru dapat diadopsi kembali. Di era itu, Polri begitu dicintai dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang dilakukan oleh Jusuf yakni: menghadirkan TNI-Polri di hati rakyat yang dikenal dengan “Kemanunggalan ABRI dan Rakyat”; mewujudkan kesejahteraan yang layak bagi semua prajurit TNI-Polri; dan, secara terus menerus meningkatkan profesionalisme seluruh jajarannya melalui pembenahan Diklat-diklat TNI-Polri.
Di era M Jusuf, tidak ada pejabat TNI-Polri yang berani main mata dengan konlomerat. Bahkan di kala itu, pernah beredar berita ketika beliau menegur Liem Soei Liong, pemilik BCA, ketika datang di kediaman Presiden Soeharto dengan pakaian seenaknya.
Kedua, keberadaan kepolisian yang langsung berada di bawah Presiden kelihatannya terjadi di hanya sedikit sekali negara di dunia. Di lingkup ASEAN misalnya, selain Indonesia, kepolisian yang langsung berada di bawah Kepala Negara hanya di Brunei dan Thailand karena polisi sebagai alat kekuasaan. Seluruh anggota ASEAN lainnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga Timor Leste.
Terakhir, pelajaran terpenting yang dapat dipetik dari kasus Sambo adalah jika seseorang mencapai kemenangan, kemewahan atau kekuasaan dengan cara jahat maka artinya sama dengan gagal karena berakhir dengan penyesalan dan kepedihan tanpa akhir.